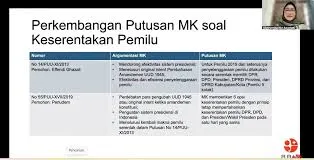ap – Konstelasi politik nasional kembali berubah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 (Putusan 135) pada 26 Juni 2025. Keputusan ini mengguncang lanskap politik Indonesia karena melegitimasi pemisahan jadwal pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal, sebuah langkah yang memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat hukum dan politisi. Putusan ini seolah menjadi babak baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia, membuka ruang untuk refleksi mendalam tentang sistem pemilu yang ideal.
Putusan 135 mengakhiri anomali pemilu serentak yang selama ini dipraktikkan, sebuah sistem yang dinilai banyak pihak justru menimbulkan berbagai krisis. Mulai dari melemahnya pelembagaan partai politik, terhambatnya upaya penyederhanaan sistem kepartaian, hingga menurunnya kualitas kedaulatan rakyat, pemilu serentak dianggap gagal memenuhi harapan. Akar masalahnya terletak pada desain sistem pemilu yang bermasalah, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pemimpin yang terpilih. Keserentakan pemilu seharusnya tidak hanya dipandang sebagai sekadar pengaturan jadwal, apalagi disederhanakan menjadi persoalan teknis dan implementasi undang-undang. Lebih dari itu, pengaturan jadwal pemilu memiliki dampak serius terhadap pemenuhan asas penyelenggaraan pemilu, serta kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, penting untuk mengesampingkan tendensi politis dan fokus pada pendekatan penafsiran yang mendasari Putusan 135.
Dalam menganalisis Putusan 135, penting untuk memahami bahwa perubahan desain pemilu dapat dilihat dari tiga pendekatan, sebagaimana diungkapkan oleh Allen Hicken (2020) dalam studinya “When Does Electoral System Reform Occur?”. Ketiga pendekatan tersebut adalah kegagalan sistematis (systematic failure), krisis katalis (catalyst crisis), dan preferensi petahana (incumbent preference). Selama ini, pemilu di Indonesia cenderung melihat preferensi petahana sebagai pendekatan yang ideal. Padahal, pendekatan ini cenderung pragmatis dan lebih mengutamakan keuntungan elektoral petahana. Akibatnya, kondisi objektif dari desain sistem pemilu seringkali dikesampingkan, dengan pertimbangan keunggulan politik menjadi faktor utama. Pendekatan kegagalan sistematis menawarkan perspektif yang berbeda, di mana perubahan desain sistem pemilu dilihat dari dampaknya. Jika sistem pemilu gagal atau tidak mampu mencapai tujuannya dan justru menimbulkan masalah, maka perubahan perlu dilakukan. Italia, misalnya, pernah menerapkan sistem pemilu proporsional untuk menyeimbangkan perwakilan di parlemen dengan perolehan suara. Namun, sistem tersebut justru melahirkan fragmentasi politik, faksionalisasi, serta nirakuntabilitas. Akhirnya, Italia mengubah sistem pemilu dari proporsional ke sistem pemilu campuran melalui referendum.